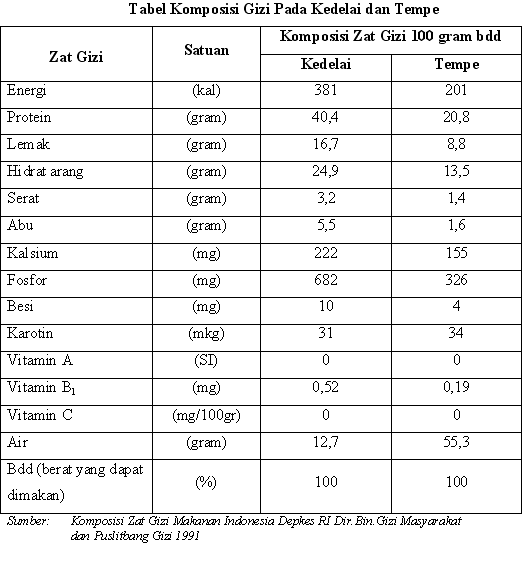Feri Fadli
FKM Jurusan Ilmu Perilaku, Universitas Sumatera Utara
Makanan fungsional memiliki beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Paling tidak ada dua hal pokok pertama, makanan itu disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman; kedua, diterima oleh konsumen berdasarkan karakteristik sensori yang dimilikinya termasuk penampakan, warna, tekstur, atau konsistensi dan cita rasa (Menristek, 2008).
Makanan fungsional menjadi topik yang menjadi perhatian sebab dari masalah defesiensi gizi yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan mengkonsumsi makanan tersebut. Data menunjukkan saat ini Indonesia berada di peringkat kelima di urutan negara dengan kekurangan gizi se-dunia. Jumlah balita yang kekurangan gizi di Indonesia saat ini sekitar 900 ribu jiwa. Jumlah tersebut merupakan 4,5 % dari jumlah balita Indonesia, yakni 23 juta jiwa (Tarigan, 2012).
Sebagaimana diketahui, masalah defesiensi gizi yang terjadi ini ternyata berdampak pada banyak hal dalam kehidupan manusia Indonesia. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 mencatat 35,7 % anak Indonesia tergolong pendek akibat masalah gizi kronis. Dengan persentasi sebesar itu diperkirakan ada 7,3 juta anak Indonesia yang menjadi pendek. Masalah gizi lain yang dihadapi yakni obesitas yang dialami oleh 15 % orang dewasa berusia 15 tahun ke atas.
Secara normatif, akar masalah kasus gizi lebih disebabkan oleh kondisi kemiskinan ekonomi yang diperparah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Walaupun dalam beberapa kasus ada juga keluarga dengan kemampuan ekonomi yang mumpuni tetapi kurang memiliki pengetahuan dalam mengelola uang untuk memenuhi pola makanan fungsional yang bergizi, sehat, berkualitas, dan tidak terlalu mahal, termasuk jenis yang mudah, murah, dan tersedia dalam masyarakat seperti tempe (Ridwan, 1988).
Istilah tempe mempunyai konotasi yang sepele, murah atau tingkat sosial yang rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena pembuatan tempe yang sangat sederhana, kurang higienis serta harganya yang murah. Citra tempe menjadi lebih menurun khususnya di zaman orde lama karena adanya pernyataan politik yang melibatkan nama tempe (Sulaiman, 1996).
Tempe adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai dan difermentasikan dengan menggunakan kapang rhizopus (ragi Tempe). Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai tebesar di Asia. Konsumsi tempe rata-rata per orang per tahun di Indonesia saat ini diduga sekitar 6,45 Kg. Sebanyak 50 % dari konsumsi kedelai Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40 % dalam bentuk tahu, dan 10 % dalam bentuk produk lain (seperti tauco, kecap, dan lain-lain) (Koswara, 1992).
Tempe memiliki kandungan zat gizi yang tinggi dan memiliki fungsi yang sangat baik di dalam tubuh. Adapun komposisi zat gizi pada tempe dapat dilihat pada tabel berikut:

Bagi orang-orang yang sedang diet, tempe merupakan makanan yang dianjurkan karena kalorinya rendah yaitu hanya 157 kal per 100 gr (beberapa makanan lain di atas 350 kal per 100 gr). Kadar karbohidratnya sangat rendah 9,4 serta tidak mengandung pati dan gula, sehingga sesuai bagi penderita diabetes, bahkan kandungan kolesterolnya tidak ada sama sekali. Dari banyaknya manfaat tersebut, banyak orang Indonesia yang mengambil peluang usaha dengan memanfaatkan tempe, termasuk membuka pabrik tempe di negara Jepang (Anonim, 2012).
Masalah yang terjadi adalah stigma tempe sebagai makanan sepele hanya menjadikannya sebagai pilihan kedua. Hal ini tidak saja akibat dari pemahaman yang ada dalam masyarakat, tingkat pengetahuan tertentu, faktor kebiasaan, juga daya beli masyarakat. Beberapa faktor ini membentuk ikatan rantai sebagai akibat gejala kehidupan sosial yang semakin kompleks. Hal ini kemudian menjadi pola umum yang diterima begitu saja.
Khusus untuk tingkat daya beli masyarakat, tentu tidak mudah untuk mengidentifikasinya terlebih berkenaan dengan masalah pangan. Namun, dengan patokan bahwa rata-rata 50 % pendapatan rumah tangga di Indonesia dihabiskan untuk konsumsi pangan, maka tidak sulit menghitung dampak kenaikan harga pangan terhadap daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Rakyat miskin sendiri menjadi fokus karena konsumsi pangan mereka bisa menghabiskan 70-80 % dari total pendapatannya (Hardjono, 2000).

Data kemiskinan menunjukkan, pada tahun 2010 angkanya mencapai 13,3 % atau sekitar 31,02 juta jiwa. Namun, sebetulnya yang bisa digolongkan orang miskin yang rawan terhadap kenaikan harga pangan lebih banyak dari itu. Kelompok ini akan terperangkap dalam kubang kemiskinan ekstrim apabila harga pangan meningkat, misalnya kenaikan 10-20%. Jika angka ini dijadikan patokan, maka hanya tersisa 23% dari pendapatan yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lainnya, seperti pakaian, rumah (listrik dan air), pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sebaliknya, jika mereka tidak ingin mengorbankan pengeluaran non-pangan, maka berarti kaum miskin harus mengurangi belanja pangannya.
Banyak penelitian di dunia telah membuktikan bahwa merokok tidak hanya merusak kesehatan, tetapi merusak ekonomi rumah tangga. Pembelian rokok dan menghisap rokok merupakan perbuatan mubazir, menimbulkan biaya berobat akibat penyakit yang ditimbulkan rokok dan asapnya, dan meningkatkan resiko kematian dini. Kerugian akibat konsumsi rokok dihitung dari jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli rokok, biaya berobat penyakit yang terkait konsumsi rokok, biaya yang hilang karena tidak bekerja sewaktu sakit, dan penghasilan yang tidak diterima anggota keluarga dari yang meninggal karena penyakit akibat rokok (Mc Gee, 2005).
Merokok tidak hanya menyebabkan penyakit bagi perokok itu sendiri melainkan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Menurut Survei Sosial Ekonomi lebih dari 90 % perokok mempunyai kebiasaan merokok di dalam rumah ketika bersama dengan anggota keluarga. Akibatnya, kerugian akibat rokok sangat tinggi padahal uang untuk membeli rokok dapat lebih berguna untuk membeli makanan bergizi atau membiayai sekolah anak dan sebagainya.
Menurut Smet (1994) ada tiga perokok yang dapat diklasifikasikan menurut banyaknya rokok yang dihisap. Tiga tipe perokok tersebut adalah:
1. Perokok berat yang menghisap lebih dari 15 batang rokok dalam sehari
2. Perokok sedang yang menghisap 5-14 batang rokok dalam sehari
3. Perokok ringan yang menghisap 1-4 batang rokok dalam sehari
Jika diasumsikan harga rata-rata satu bungkus rokok adalah Rp. 10.000,- dan seorang perokok menghabiskan satu bungkus rokok perhari, tentu saja biaya konsumsi rokok ini akan sangat tinggi jika konsumsi rokok dilakukan setiap hari. Lain lagi jika berbicara tentang biaya yang akan dikeluarkan akibat dari rokok itu sendiri. Adapun maksud dari biaya untuk membeli rokok dapat lebih berguna untuk membeli makanan bergizi jika kemudian biaya konsumsi rokok dirubah untuk membeli makanan fungsional yakni tempe.
Harga tempe yang murah yakni Rp. 2.000,- tentu akan menjadi pilihan yang mudah untuk dikonversikan dari biaya rokok harian. Dapat dilihat harga satu bungkus rokok setara dengan harga lima bungkus tempe. Jika uang konsumsi rokok diarahkan untuk membeli tempe, tentu kebutuhan gizi harian keluarga akan terpenuhi dan biaya akibat konsumsi rokok akan hilang. Khusus untuk mereka yang susah untuk mengubah kebiasaan merokok, konversi biaya membeli tempe ini dapat dilakukan bertahap, sampai berujung pada perubahan perilaku merokok.
Bahkan dari perkalian apapun, kebiasaan membeli tempe ini akan jauh lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan membeli rokok. Dengan adanya tempe dan kandungan gizi yang dimilikinya, serta harga yang sangat terjangkau, tentu dapat menyelamatkan masyarakat miskin dari malagizi (malnutrition). Karena, konsumsi terhadap tempe sangat baik diberikan kepada segala kelompok umur. (Kasmidjo, 1990).
Sebagai dasar penguatan dari asumsi ini, mungkin perlu ditampilkan berbagai manfaat yang diperoleh dari tempe, sebagai berikut:
1. Adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein, lemak, dan karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh dibandingkan yang terdapat dalam kedelai. Oleh karena itu, tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur (dari bayi hingga lansia), sehingga bisa disebut sebagai makanan semua umur (Hermana, Mien K & Karyadi D, 1996).
2. Senyawa dalam tempe diduga memiliki aktivitas anti penyakit degeneratif (aterosklerosis, jantung koroner, diabetes melitus, kanker, dll) yakni Vitamin E, Karatenoid, Superoksida desumutase dan isoflavon. Dimana vitamin E dan karotenoid adalah antioksidan non enzimatik dan lipolitik yang mampu membeikan satu ion hidrogen kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut stabil dan tidak ganas lagi (Anonimous, 2004).
3. Ternyata ekstrak tempe yang digunakan dalam percobaannya amat efektif untuk membunuh bakteri Bacillus Subtilis, Vibrio Cholera Ettor, dan Staphylococcus aureus. Hasil riset memperlihatkan, ekstrak tempe dalam kadar larutan memiliki aktivitas anti mikroba yang tinggi, dimana kepekaan daya hambat tertinggi adalah pada bakteri Vibrio cholerae Eltor. Dengan demikian, ekstrak tempe dimungkinkan pengembangannya untuk antibiotik di masa depan (Sarwono, 1987).
4. Tempe mengandung asam lemak tidak jenuh yang mampu mencegah pengapuran dalam pembuluh darah akibat asupan lemak atau kholesterol berlebihan juga mengandung anti oksida berupa isoflavon dan zat ini mampu menormalkan tekanan darah tinggi, di samping melancarkan sirkulasi darah di seluruh tubuh. Dampaknya amat positif untuk tercapainya kondisi jantung yang sehat. Sedangkan zat isoflavon dengan segala turunannya mepunyai efek-efek kardiovaskuler, seperti efek terhadap sirkulai darah pada pembuluh mikro (Anonimous, 2004).
5. Tempe juga mengandung cukup banyak lesitin dan niasin, yakni dua zat yang diketahui mampu mencegah kenaikan kadar kolesterol pada serum darah, disamping menurunkan resiko timbulnya atherosklerosis (pengerasan pembuluh darah) (Hermana, Mien K & Karyadi D, 1996).
6. Tempe juga merangsang kekebalan tubuh terhadap E.coli, bakteri penyebab diare. Lazimnya penyakit ini terjadi akibat buruknya sanitasi lingkungan dan kurang bersihnya makanan. Untuk mengatasinya, berikan pertolongan pertama dengan memberi si sakit racikan tempe. Caranya, tempe dikukus lalu dihaluskan, kemudian dicampur dengan air tajin dan garam (Hermana, Mien K & Karyadi D, 1996).
Sekali lagi, bahwa konversi nilai gizi tempe melalui perubahan perilaku merokok merupakan pilihan yang bijak dan kreatif yang dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Kebiasaan ini dapat dilakukan untuk membantu pemenuhan gizi keluarga sekaligus mengurangi biaya konsumsi rokok dan biaya pengobatan akibat mengkonsumsi rokok. Semua ini sangat sederhana hanya dengan melalui kebiasaan mengkonsumsi makanan fungsional unik yang bernama tempe.
REFERENSI
Anonim, 2004. Biokimia Tempe. Pustidaka Sinar Harapan: Jakarta.
Anonim, 2012. Sukses Merintis Usaha Tempe di Negeri Sakura. Diakses dari http://bisnisukm.com/sukses-merintis-usaha-tempe-di-negeri-sakura.html pada 16 Mei 2012.
Hardjono, 2000. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Untuk Hidup Sehat. Faperta IPB: Bogor.
Hermana, M.K., 1996. Pengembangan Teknologi Tempe dalam Sapuan dan Sutrisno (ed), Bunga Rampai Tempe. Yayasan Tempe Indonesia: Jakarta.
Kasmidjo, 1990. Tempe, Mikrobiologi dan Biokimia Pengolahan Serta Pemanfaatannya. Unika Soegijapranata-Press: Semarang.
Koswara, S., 1992. Teknologi Pengolahan Kedelai. Pustidaka Sinar Harapan: Jakarta.
Mc Gee, dkk., 2005. Is Cigarette Smoking Associated With Suicidal Ideation Among Young People?: The American Journal of Psycology. Diakses dari http://.proquest.com/[on-line] pada 15 Mei 2012.
Ridwan, Endi., 1988. Tempe Sebagai Bahan Makanan, Makanan dan Obat. Medika: Jakarta.
Sarwono, B., 1987. Membuat Tempe dan Oncom. Penebar Swadaya: Jakarta.
Smet, B. 1994. Psikologi Kesehatan. Semarang: PT. Gramedia.
Tarigan, Mitra., 2012. RI Negara Urutan ke 5 Warga Kurang Gizi. Diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2012/01/18/173378104/Indonesia-Peringkat-5-Kekurangan-Gizi-Sedunia 2012 pada 16 Mei 2012.
Sulaiman. 1996. Skala Usaha Bisnis Tempe di Indonesia. Bunga Rampai Tempe Indonesia: Jakarta.
Winarno, F.G., 1996. Kimia Makanan dan Gizi. Gramedia Pustidaka Utama: Jakarta